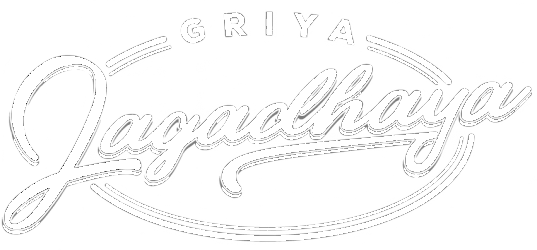Pascagempa pertama di Lombok pada 29 Juli 2018, beberapa kawan yang bermukim di Lombok mengabarkan situasi dan kondisi lewat sebuah grup WhatsApp di mana kami tergabung di dalamnya. Ada yang rumahnya hampir rata dengan tanah, ada yang masih berdiri namun dengan retak di sana-sini.
“Di Kecamatan Sambelia dan Sembalun banyak korban. Sementara di Kecamatan Suela masih aman,” kata Eros.
Selang tiga jam kemudian, kawan yang lain yang tinggal di Lombok Utara, Hamdi, mengirimkan foto, sebuah tenda besar dengan simbol palang merah di atapnya. “Para pengungsi yang dievakuasi di lapangan Ancak, Desa Karang Bajo,” terangnya.
“Wah, ada korban di Karang Bajo?” tanya saya.
“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuma bangunan saja. Mohon doa dari kawan-kawan,” balas Hamdi.
Dua jam kemudian, Fikri, menimpali percakapan: “Sudah saya kirim video korban bencana langsung dari TKP. Maaf telat soalnya baru pulang liputan.”
Keesokan harinya, dua pesan membunyikan ponsel saya. Kali ini dari Hafiz. “Anak-anak kita membutuhkan logistik, obat-obatan, minyak telon, dan lain sebagainya. Selain itu juga mereka membutuhkan pendampingan untuk mengurangi trauma. Kondisi psikis anak-anak di sini sangat memprihatinkan. Tidak ada yang berani masuk pekarangan rumah mereka karena masih sangat trauma, terangnya.”
Seminggu kemudian, tepatnya 5 Agustus 2018, gempa cukup besar kembali mengguncang Lombok. Bermagnitudo 7, lebih besar dari 29 Juli yang “hanya” 6,4. Gempa yang ke sekian kalinya ini hampir meratakan Lombok bagian timur dan utara.
“Tembok kelilingnya tumbang, mas,” kata Fikri, “Malam baru ke pengungsian tanpa tenda.” Rumah Fikri yang sebelumnya bertahan dari gempa akhirnya kandas juga.
Setelah hari itu, lalu lintas percakapan menjadi sangat intens; ada yang marah, ada yang mengeluh, ada yang kecewa, dan ada pula yang berbagi semangat. Yang pasti informasi tentang situasi terbaru di tempat masing-masing berseliweran.
Eros, Fikri, Hamdi, dan Hafiz adalah pegiat media komunitas di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hajad Guna Roasmadi atau Eros dan Fikrillah M. Sanusi bergiat di media komunitas Speaker Kampung di Lombok Timur, sementara Hamdi Hidayat dan Miftahul Hafiz pegiat radio komunitas Primadona FM di Lombok Utara. Sejak gempa pertama terjadi, mereka cukup giat mengabarkan perkembangan situasi pascagempa, baik lewat jaringan pribadi seperti WhatsApp, maupun media komunitas yang mereka kelola. Mereka adalah salah dua sumber informasi saya, dari sekian banyak media yang meliput-laporkan bencana gempa di Lombok.
Dalam situasi darurat bencana, keberadaan warga sebagai pengelola informasi sangat penting. Sama halnya dengan relawan logistik atau medis, relawan informasi pun berperan penting dalam penyediaan informasi di lapangan. Dalam banyak kasus, ketiadaan relawan informasi membuat penanganan bencana lebih sulit. Pengumpulan informasi-informasi primer seperti wilayah mana saja yang terdampak, berapa jumlah korban jiwa dan yang masih yang bertahan, apa saja yang dibutuhkan penyintas di pengungsian dan semcamnya kerap mengandalkan pihak ‘luar’ yang juga membutuhkan waktu untuk membaca medan. Sementara data sedang dikumpulkan, warga sudah harus mencari tempat bernaung atau mengisi perut untuk bertahan hidup.
Jarak waktu inilah yang kerap menimbulkan kekacauan di fase-fase awal penanganan bencana. Kasus penjarahan seperti yang diinformasikan terjadi di Palu, Sulawesi Tengah (1/10/2018) dan Lombok pada hari-hari awal pascabencana, rentan terjadi.
Ambil contoh soal informasi distribusi bantuan di minggu pertama tanggap darurat gempa Lombok. Karena kendala armada, saat itu BNPB mengimbau setiap perwakilan posko pengungsian di desa untuk mengambil bantuan logistik ke posko utama di Tanjung, ibu kota Kabupaten Lombok Utara, yang jaraknya relatif jauh bagi beberapa desa terdampak. Keputusan ini tampaknya diambil tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi penyintas yang jelas-jelas defisit logistik dan tenaga usai dihantam gempa—kasus ini belakangan terjadi juga di Palu. Hamdi, saat saya hubungi mengaku tidak tahu adanya imbauan tersebut. “Lagipula, tidak bisa juga kita ngambil di Tanjung. Jangkauan jauh.. kalo mereka yang antar akan kami terima sudah. Kami juga tidak ada armada,” katanya.
Jarak Desa Karang Bajo, tempat Hamdi tinggal dengan ibu kota kabupaten Lombok Utara mencapai 44 kilometer atau sekitar satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Dari situ terlihat bahwa sistem komunikasi yang digunakan tidak efektif. Informasi dari atas tidak terjamin lancar sampai ke bawah, meski katanya imbauan sudah disampaikan kepada camat dan kepala desa masing-masing. Kasus ini tidak hanya terjadi di satu daerah bencana.
Media massa tradisional pun tidak menjadi jawaban atas persoalan ini. Sebagai contoh, alih-alih membantu parapihak menjelaskan skema penanganan dan distribusi bantuan, media massa tradisional lebih tertarik dengan sensasi dari peristiwa penjarahan yang terjadi—kasus penjarahan di Palu kemudian menjadi perhatian media internasional dan memicu rasa antipati orang-orang di luar daerah bencana.
Celah ini yang sebetulnya bisa diisi oleh media komunitas dalam situasi bencana; menjadi relawan informasi. Ada beberapa keuntungan yang didapat bila melibatkan media komunitas dalam penganganan bencana. Pertama, media komunitas sudah hapal medan. Pegiat media komunitas adalah warga setempat yang bisa dipastikan menguasai dan mengetahui medan dengan baik. Kedua, pegiat media komunitas memiliki kedekatan dengan warga lain karena mereka adalah bagian dari masyarakat tersebut. Ketiga, dalam situasi bencana pegiat media komunitas punya motivasi besar untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Inilah bekal militansi mereka ketika mencari berita di lapangan. Militansi ini tergambar dalam tulisan Fikri tentang pengalamannya meliput gempa Lombok :
“Pengalaman saya meliput bukan tanpa kesulitan. Selain karena saya sendiri adalah korban dalam peristiwa alam ini, saya sering menemui hambatan saat mencari berita. Pernah di perjalanan saya kehabisan bensin, lapar dan haus karena tidak ada warung makan yang buka atau kehabisan uang. Namun, di saat-saat seperti itu, ada saja orang yang datang membantu. Ada yang memberikan bensinnya cuma-cuma.
Yang sangat menjengkelkan adalah saat sedang melakukan liputan, android usang yang saya pakai untuk mengambil gambar kehabisan baterai. Ada power bank namun tidak bertahan lama. Akhirnya dengan mengabaikan sedikit rasa malu, dan tanpa menghilangkan rasa segan, saya meminjam ponsel orang lain untuk memotret. Pikir saya, momen itu penting untuk saya kisahkan nanti.”
Douglas Paton dan Melanie Irons dalam Communication, Sense of Community, and Disaster Recovery: A Facebook Case Study (2016), menjelaskan bahwa situasi yang berbeda di lapangan berdampak pada tidak efektifnya komunikasi dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Dalam konteks ini, tulis mereka, tidak mengherankan bahwa alasan dominan dari orang yang beralih ke media sosial, demi mendapatkan informasi, adalah karena ketidakpuasan terhadap informasi yang diberikan oleh media tradisional. “Badan berwenang dan sumber media massa konvensional tidak dapat merespons secara efektif kebutuhan informasi spesifik, lokal, dan berkembang dari populasi yang terkena dampak,” tulisnya.
Speaker Kampung, media komunitas yang berbasis di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, misalnya, sudah mengunggah laporan mengenai dampak gempa hanya beberapa jam setelah guncangan. Fikri yang aktif mengabarkan kondisi desa-desa di Kecamatan Sambelia bercerita bagaimana ia bergerak mencari informasi tak lama setelah gempa terjadi :
“Sekitar 20 menit kemudian [setelah gempa] … saya langsung terjun ke Puskesmas, lalu wawancara keluarganya, khususnya mengenai kronologi kejadian. Sewaktu di Puskesmas itu, rekan di Speaker Kampung, Eros, menelepon untuk menanyakan update situasi. Karena saya tidak bisa menulis [saat itu], ya saya langsung laporkan untuk ditulis sama Eros, lalu tulisan itu diunggah ke Fanspage Speaker Kampung, baru kemudian ke website. Saya ikuti korban sampai dibawa kembali ke rumahnya di Desa Sugian yang tidak terlalu jauh dari desa saya, saya videokan juga, saya juga sempat wawancara Kepala Desa Sugian.”
Komunikasi itu yang kemudian membuahkan artikel pertama mereka tentang gempa Lombok. Berita itu diberi judul “Rumah Rusak dan Dua Orang Korban Akibat Gempa di Sambelia”, terbit sekitar pukul 08.53 WITA di laman Fanpage Facebook Speaker Kampung, selang dua jam dari gempa pertama. Pegiat Speaker Kampung lainnya, Sanusi, juga melakukan hal yang sama di kecamatan lain. “Saya liputan di Kecamatan Wanasaba. Biasanya kemarin kan liputannya ditulis, tetapi sekarang karena keadaan mendesak pakainya video HP, soalnya hasilnya lebih jelas dan kelihatan, orang bisa langsung lihat kondisinya seperti apa. Kalau video di-share, mereka (warga terdampak) jadi terbantu. Mereka senang di-video-in, malah pada minta diliput.”
Di hari pertama gempa, Speaker Kampung menurunkan enam berita dalam bentuk tulisan dan/atau video. Pada hari-hari setelahnya, Speaker Kapung merilis paling sedikit tiga berita dalam bentuk tulisan maupun video. Hampir seluruh informasinya seputar kondisi penyintas di tenda-tenda darurat di empat kecamatan—Suela, Wanasaba, Pringgabaya, Sambelia—di Lombok Timur.
Menurut Eros, liputan Speaker Kampung yang disebar melalui Fanspage Facebook mendapat respons positif dari warga. Banyak yang membagikan dan yang menelepon memberikan laporan. Selain itu, ada juga yang memberikan bantuan. Eros mencontohkan, sebuah video hasil liputan Speaker Kampung soal warga yang mengungsi di bukit, di daerah sekitar Obel-Obel (wilayahnya terpencil sehingga sulit terjangkau bantuan) dijadikan rujukan donatur untuk mengirim bantuan ke daerah tersebut.
Andai pihak berwenang mau merujuk informasi dari bawah, keterlambatan distribusi logistik mungkin dapat diminimalkan, karena situasi dan kebutuhan dapat diperkirakan secara lebih akurat.
Media komunitas Primadona FM punya cerita berbeda. Pada 3 September, Fanpage Rakom Primadona FM merilis informasi mengenai janji bantuan pemerintah kepada korban gempa Lombok. (Radionya sendiri tidak beroperasi selain karena studio rawan roboh, Primadona masih terkendala izin siaran). Isinya kurang lebih mengurai poin-poin mengenai bantuan biaya jaminan hidup, biaya isi rumah dan biaya rekonstruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018 serta pernyataan Menteri Sosial yang saat itu menjabat, Idrus Marham. Unggahan ini mendapat respons cukup besar dari para penyintas gempa pengguna Facebook. Puluhan komentar masuk dan dibagikan (share) lebih dari 300 kali. Kebanyakan dari mereka menanyakan kesahihan informasi tersebut dan seberapa pasti bantuan itu akan turun. Ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai bantuan belum sampai ke telinga warga di lapisan bawah, meski sudah dipublikasikan lewat media massa.
Informasi yang dikumpulkan oleh para pegiat media komunitas sebetulnya merupakan data-data primer yang dibutuhkan dalam setiap penanganan bencana. Mereka bahkan bisa menjangkau tempat-tempat yang muskil digapai oleh media massa yang datang saat kejadian, yang biasanya menyasar titik-titik utama seperti posko induk, kantor pemerintah, dan sejenisnya. Inilah salah satu kekhasan media komunitas yang sebagian sarjana media menyebutnya sebagai hiperlokal (hyperlocal).
Tidak hanya itu. Satu lagi keistimewaan media komunitas adalah perannya sebagai pengentas masalah (problem solver). Ada beberapa faktor yang membuat media komunitas berpotensi melakukan hal tersebut. Pertama, mereka adalah bagian dari komunitasnya, artinya masalah komunitas adalah masalah mereka juga. Kedua, mereka paham betul apa masalah yang sedang dihadapi komunitasnya.
Pada 30 Juli, sehari setelah gempa pertama, saya berkomunikasi dengan Eros untuk menanyakan perihal kebutuhan warga penyintas di tenda darurat. Selain makanan, “ada juga kebutuhan khusus untuk anak-anak. Butuh relawan untuk trauma healing,” katanya.
Selang beberapa hari kemudian, pada 4 Agustus, saya mendapati video mereka saat sedang bermain dan menghibur anak-anak di Dusun Melempo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia sudah diunggah di Facebook. Para pegiat Speaker Kampung menjawab kebutuhan anak-anak penyintas akan tenaga trauma healing. Tentu saja, di luar aksi tersebut, mereka juga menggalang dana dan menyalurkan logistik ke beberapa titik pengungsian di Lombok Timur, sebagaimana dilakukan oleh pegiat media komunitas Primadona FM di Lombok Utara dengan membentuk komunitas temporer bernama Pemuda Ancak Tanggap Bencana (PATB).
Memasuki masa transisi ke pemulihan, Speaker Kampung mengubah strategi. Mereka tidak lagi berkutat pada penyaluran logistik melainkan mulai menginisiasi hunian sementara untuk para penyintas gempa dengan memanfaatkan bahan baku alam seperti kayu, bambu dan daun kelapa.

Dalam keterangan foto di Facebook yang diunggah pada 8 September 2018, mereka menulis, “Enam unit hunian sementara telah dibangun Speaker Kampung. Dengan memanfaatkan bahan lokal, tentu biayanya sangat murah. Untuk satu bangunan biayanya Rp 200.000-500.000.”
Bagi saya, selama penanganan gempa Lombok, baik Speaker Kampung maupun Primadona FM telah berhasil memperlihatkan bagaimana menjadi warga berdaya di tengah kondisi bencana.
Pekerjaan rumah berikutnya
Kendati demikian ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ke depan. Pertama, soal pelibatan media komunitas dalam skema penanganan bencana. Meski militansinya tak dimungkiri, apresiasi terhadap kerja-kerja mereka masih terbilang minim. Untuk kasus Lombok, berita-berita yang diproduksi belum menjadi rujukan para pihak yang terlibat dalam proses penanganan bencana. Media komunitas boleh jadi tidak dapat meng-cover seluruh daerah terdampak bencana, namun media komunitas dapat membantu menghimpun data yang lebih akurat untuk daerah-daerah tertentu. Selain membantu proses penanganan bencana oleh pemerintah, pelibatan media komunitas bisa jadi sebentuk emansipasi terhadap warga. Sebab selama ini warga lebih sering diposisikan sebagai korban alih-alih dirangkul agar menjadi warga berdaya.
Kedua, soal penguatan kapasitas media komunitas. Yang perlu disadari adalah kebanyakan pegiat media komunitas tidak pernah mengenyam pendidikan formal terkait media atau jurnalistik. Mereka belajar secara otodidak, sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi dapat dimaklumi. Kendati demikian, Primadona FM dan Speaker Kampung tidak bisa disamakan dengan warganet yang asal menyebarkan berita palsu alias hoax dari sumber antah berantah—Speaker Kampung bahkan beberapa kali coba mengklarifikasi kabar sumir yang beredar seperti penjarahan logistik oleh warga dan kisah berbau mistik, tentang telapak kaki dan tangan yang muncul di tembok-tembok reruntuhan rumah warga. Mereka tetap mencoba menerapkan prosedur jurnalistik sejauh yang mereka pahami.
Ke depan perlu ada yang menemani mereka dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana meliput peristiwa bencana scara memadai. Siapa yang berperan di sini? Tentu saja semua pihak. Bisa lembaga non-pemerintah, asosiasi jurnalis profesional, bahkan mungkin Dewan Pers. Intinya, media komunitas merupakan manifestasi semangat baik warga akar rumput yang harus dirawat. Oleh karena itu,perhatian dari semua pihak yang memiliki kepakaran di bidang bencana untuk berbagi pengetahuan dengan pegiat media komunitas diperlukan—walaupun bukan tidak mungkin mereka belajar secara mandiri.
Dengan begitu, seiring dengan wacana penguatan mitigasi bencana di Indonesia yang marak (lagi) belakangan, pemberdayaan media komunitas dalam situasi bencana bisa jadi salah satu upaya yang patut dipertimbangkan.[]