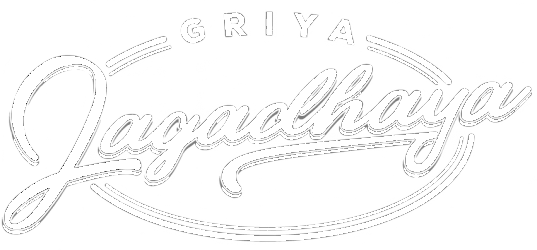Suatu ketika, sekitar tahun 2015, seorang kawan, seorang jurnalis warga di Lombok menelepon saat saya baru akan memulai rutinitas di kantor.
“Mas, bisa bantu saya?”
“Ada apa, pak?”
“Saya sedang di kantor polisi.”
Saya terkejut dan langsung keluar ruangan, mencari tempat yang lebih tenang, “Lho, kenapa?”
Kemudian dia bercerita bahwa sedang mengurus aduan yang melibatkan dirinya. Seorang warga, sebut saja Jali—saya tidak yakin siapa tepatnya, tokoh di daerah itu, merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh kawan saya ini lewat berita yang dia buat. Saya bertanya padanya, coba merunut peristiwa yang sedang menjeratnya. Dia menulis berita tentang sebuah kasus di desanya yang melibatkan si Jali dengan mengutip pernyataan polisi. Tapi Jali tidak terima namanya dikutip sehingga mengadukannya ke polisi. Saya dan teman-teman di kantor coba membantunya dengan memeriksa berita yang dia tulis, memastikan tak ada kekeliruan. Kami juga mencari orang yang sekiranya bisa membantu, bersiap jika perkara tersebut dibawa lebih jauh. Singkat cerita, karena bukti lemah, polisi kesulitan mengusut lanjut kasus tersebut. Masalah akhirnya diselesaikan dengan “cara kekeluargaan”.
Di kesempatan berbeda dia mengaku sering mendapat ancaman dan teror. Saya tidak heran karena beritanya memang kerap mengangkat persoalan-persoalan di desanya, yang secara langsung maupun tidak menyinggung kekuasaan lokal. Namun, karena orangnya ‘bebal’, dia tak menggubris ancaman itu. Kadang menjadikannya sebagai lelucon, bahkan menantang orang yang mengancamnya. “Kalo memang berita saya salah, sila buktikan,” katanya waktu menceritakan ulang pada saya.
Sebetulnya, menjadi jurnalis warga dan pengelola media komunitas—dua hal berbeda namun berkait erat—bukanlah hal gampang. Ancaman yang mereka hadapi sehari-hari sangat riil. Kasus yang saya ceritakan barusan adalah salah satunya. Cerita lainnya, misal, hanya karena memberitakan perkelahian antarwarga di desanya, seorang jurnalis warga ‘disemprot’ oleh perangkat desa. Alasannya karena berita itu dianggap akan merusak nama desa tersebut. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa hari sebelum saya menuliskannya di sini.
Jurnalis warga, saya boleh bilang, adalah orang-orang nekat. Kalau mereka tidak ‘bebal’, mungkin mereka sudah mundur. Tapi toh mereka menolak. Alasan mereka sederhana, “kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memberitakan ini?” Disadari atau tidak, alasan mereka mungkin menyindir praktik media arus utama yang cenderung terpusat dan seragam. Motivasi para jurnalis warga atau pegiat media komunitas, biasanya, dilandasi oleh harapan untuk memperbaiki yang tidak beres di tempatnya tinggal.
Kebanyakan media komunitas beroperasi di pelosok, daerah yang jarang dijangkau oleh media ‘nasional’, bahkan media lokal. Lombok, misalnya, jika bukan karena ada peristiwa yang menghebohkan seperti gempa tempo hari, mungkin media arus utama tidak tertarik untuk datang—kecuali untuk liputan pariwisata. Media komunitas ada, salah duanya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan warga di tempat mereka tinggal. Terlebih dulu, ketika internet belum semasif sekarang, media komunitas, menjadi andalan warga mengisi kebutuhan hiburan dan informasi. Di daerah dengan akses informasi terbatas, media komunitas berperan mengorganisir informasi “dari mulut-ke-mulut”, menjadi berita tertulis (cetak atau daring) atau tersiarkan (radio). Memastikan berita “kata tetangga” benar adanya dengan pendekatan jurnalistik.
Namun, sialnya, keberadaan jurnalis warga dan media komunitas kerap dipandang sebelah mata.
Belum lama saya membaca pernyataan seorang jurnalis yang bekerja untuk sebuah media besar Jakarta pada sebuah artikel di media alternatif. “Ini yang membedakan jurnalis warga dengan wartawan. Mungkin wartawan sedikit terlambat datang ke lokasi. Tapi disiplin verifikasi menentukan sebuah berita. Jurnalis warga bisa saja bilang tabrak lari pada saat kesempatan pertama mengunggah. Tapi wartawan bisa punya versi lain, misalnya lelaki yang tersungkur ternyata teroris yang jadi buronan.” Jujur saja, saya agak terganggu dengan pernyataannya. Seolah tidak ada jurnalis warga yang tidak menerapkan disiplin itu, dan sebaliknya, seolah tidak ada wartawan yang melanggar aturan itu; nyatanya, ada bejibun berita ditulis oleh wartawan yang sebatas mencomot pernyataan narasumber A atau B. Alih-alih memverifikasi pernyataan narasumber (jurnalisme verifikasi), wartawan malah kerap melakukan apa yang disebut Bill Kovac dan Tom Rosenstiel sebagai jurnalisme pernyataan (2012: 37-46). Lebih buruk lagi, jurnalisme kaum kepentingan, seperti yang dipraktikkan ‘wartawan’ dari media-media massa partisan.
Ketika di sini jurnalis warga dan karyanya masih dianggap ‘receh’, di tingkat internasional pengakuan terhadap jurnalis warga jauh lebih baik. Momen puncaknya adalah ketika seorang jurnalis warga asal Mesir bernama Wael Abbas meraih Knight International Journalism Award dari International Center for Journalists (ICJ) pada 24 Agustus 2007, berkat karya jurnalistiknya tentang gejolak sosial-politik di negaranya pada rentang 2004-2005. Karyanya juga kemudian menjadi rujukan media massa dari berbagai negara. Kasus Wael, atau Yoani Sanchez asal Kuba yang meraih penghargaan serupa pada 2014, menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi jurnalis, meski tanpa lisensi lulus uji kewartawanan atau kartu pers dari perusahaan media.
Reportes Without Borders, sebuah lembaga non-pemerintah yang konsisten mengadvokasi dan mempromosikan hak atas informasi sejak 1985, sejak tahun 2000 memasukkan kategori ‘jurnalis warga’ dalam setiap laporan tahunannya. Saya menafsir dengan dimasukkannya jurnalis warga sebagai subjek, kerja-kerja jurnalistik tidak lagi dianggap sebagai wilayah spesialis orang yang menyandang status wartawan. Jurnalisme dengan demikian diposisikan sebagai rumus atau metode, bukan pekerjaan semata.
Dalam Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi (2012), ada pendapat Bill Kovac dan Tom Rosenstiel yang menurut saya menarik dan bisa jadi bahan renungan orang-orang yang lebih suka meliyankan jurnalis warga alih-alih merangkulnya: “Cara yang kami tawarkan di sini tentang bagaimana warga bisa berperan sebagai editor untuk diri sendiri, yang lebih cerewet dan arif, bukanlah formula ketat. Sebaliknya, ia dimaksudkan untuk menjelaskan ide, membuka cara berpikir tentang informasi. Kami berharap ini membuat orang jadi lebih sadar atas konsumsi dan evaluasi mereka terhadap berita, tak peduli apakah mereka wartawan atau bukan dengan cara sama ketika belajar aljabar, kimia, atau bahasa Inggris di sekolah membantu kita menjalani aktivitas keseharian, meski kita tak menjadi matematikawan, ahli kimia, atau profesor bahasa Inggris.”
Dalam diskusi “Ketika Jurnalis Dipidana: Bagaimana Masa Depan Media Komunitas?” beberapa waktu lalu, ada pendapat Roy Thaniago (Remotivi) yang menurut saya menarik. “Sejarah pers kita dimulai dengan orang-orang tidak profesional. Tidak ada yang berprofesi sebagai wartawan murni, ada yang sebagai pedagang kelontong, petani dan lain-lain,” kata Roy. Di benak saya muncul kemudian pertanyaan: lalu, sejak kapan wartawan, khususnya di Indonesia, menjadi privilese orang-orang tertentu? Spontan saya meyakini, “ya, tentu saja sejak berlakunya rezim tenaga kerja upahan.” Namun untuk memastikannya perlu penelusuran lebih jauh.
Menjadi jurnalis warga sama menantangnya seperti jurnalis yang bekerja untuk perusahaan media. Sama-sama bekerja dengan risiko jika materi beritanya berpotensi ‘mengusik’ orang atau kelompok tertentu. Laporan Reporters Without Borders, sepanjang 2018, di seluruh dunia, ada 10 jurnalis warga yang tewas dan 143 dipenjara karena aktivitasnya. Dalam laporan itu memang tidak ada yang terjadi di Indonesia, kasus biasanya terjadi di daerah yang sedang mengalami konflik seperti Suriah. Tetapi seperti yang saya ceritakan di awal, ancaman-ancaman terhadap jurnalis warga dan media komunitas justru kerap terjadi tanpa sepengetahuan kita.
Dalam banyak situasi, jurnalis warga betul-betul tanpa perlindungan sama sekali. Jika bermasalah, Dewan Pers atau asosiasi profesi jurnalis tidak akan serta merta membela mereka.
Kok bisa? Bukankah konstitusi kita menjamin warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia? Pada praktiknya, UUD 1945 hanya tinggal teks belaka. Hingga saat ini, tidak ada regulasi yang bersifat operasional, yang menjamin aktivitas jurnalis warga maupun pegiat media komunitas. Jika pun ada, UU Penyiaran misalnya, ruang gerak media komunitas sangat sempit dan mahal. Begitu juga dengan UU Pers yang cuma berlaku bagi wartawan yang bekerja untuk perusahaan media. Masa tidak ada peran warga di UU Pers? Ada, tapi sebatas konsumen saja, atau paling banter jadi pemantau (UU Pers Pasal 17).
Contoh kasus terbaru adalah pemidanaan jurnalis media alternatif daring Serat.id, Zakki Amali. Dia dilaporkan ke polisi oleh pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan tudingan melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menulis berita tentang dugaan plagiasi oleh Rektor Unnes.
Pihak kampus menyebut “empat artikel blog yang ditulis ZA pada tanggal 30 Juni 2018” adalah “berita palsu atau hoax.” Selain itu, Zakki juga dianggap, “telah memproduksi artikel yang disebarkan melalui Facebook, Twitter dan Youtube yang menyebabkan kerugian bagi Rektor UNNES secara pribadi maupun kelembagaan. Secara pribadi, Rektor Unes namanya telah tercemar sebagai seorang pribadi, kepala rumah tangga dan akademisi,” (Unnes.ac.id, 24 Agustus 2018)
Melansir pemberitaan Tempo.co, pihak kampus mempermasalahkan Serat.id yang belum berbadan hukum dan belum terverifikasi di Dewan Pers. Status Zakki yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) juga dipersoalkan, karena itu Unnes merasa tidak perlu memberikan hak jawab kepada serat.id.
Zakki memang bukan jurnalis warga. Dia adalah anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang yang notabene merupakan konstituen Dewan Pers. Tapi ‘modal’ itu ternyata tidak cukup. Penggugat justru mempermasalahkan ketiadaan ‘sertifikat’ serat.id dan Zakki sebagai media dan jurnalis. Nah, jika media dan jurnalis yang memiliki jaringan ke asosiasi jurnalis seperti AJI dan Dewan Pers saja bisa mengalami kasus demikian, bagaimana dengan media komunitas dan jurnalis warga? Saya kira kita semua sudah tahu jawabannya.
Jurnalis warga dan media komunitas bisa dibilang bonek, bondo nekat, alias modal nekat. Dengan modal nekat bukan berarti mereka menjalankan perannya secara serampangan dan mengabaikan aturan dan nilai yang berlaku dalam dunia jurnalistik. Dalam mencari dan menulis berita, kaidah dan kode etik jurnalistik tetap menjadi pegangan utama para jurnalis warga. Jurnalistik sebagai sebuah metode memang semestinya menjadi pegangan bagi siapa pun, bahkan bagi orang-orang yang tidak bergelut di bidang media.
Apa yang menimpa Zakki Amali dan Serat.id adalah ilustrasi gamblang bagaimana selembar sertifikat lebih berarti ketimbang substansi beritanya itu sendiri. Bagi saya ini bukan persoalan yang bersifat kasuistik, melainkan sistemik. Ada bolong besar dalam hal pemenuhan hak warga atas informasi—tidak sekadar mengonsumsi, tapi juga memproduksi. Karena itu harus ada perubahan cara pandang atas jurnalisme. Meminjam kredo mendiang Rusdi Mathari, karena jurnalisme (semestinya) bukan monopoli wartawan.[]